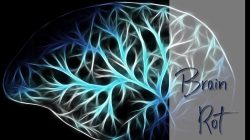Oleh: Adi Arwan Alimin
(Penulis/Pegiat Literasi)
LITERASI merupakan kunci penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan kompetitif di era globalisasi. Namun, tingkat literasi Indonesia khususnya di beberapa daerah masih menjadi tantangan besar. Melihat kondisi ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Gubernur Dr. Suhardi Duka, memperkenalkan program wajib membaca 20 buku bagi siswa SMA dan SMK sebagai syarat kelulusan.
Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Provinsi Sulbar berada di urutan 26. Sulawesi Barat dengan poin: 64,86 (detik.com, 2024). Jogyakarta tercatat di urutan pertama dengan skor 73,27 poin, sedang Papua di urutan 34 dengan skor 60,58 poin.
Program membaca 20 Buku ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kuantitas membaca, tetapi juga membangun kualitas literasi yang berdampak positif jangka panjang. Ide ini mendapat sambutan luas tidak hanya di Sulbar namun secara nasional. Pertanyaannya, bagaimana arah dan dampak program ini, serta potensi menghadapi tantangan literasi di era digital?
Program Baca 20 Buku merupakan langkah progresif untuk menumbuhkan minat baca dan budaya literasi yang selama ini masih menjadi kendala di banyak wilayah. Langkah strategis ini diperkuat oleh penetapan dua buku wajib yang mengangkat kisah tokoh lokal seperti Andi Depu, dan Baharuddin Lopa, sehingga sekaligus menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap identitas budaya daerah.
“Dua tokoh ini memiliki keteladanan yang patut ditiru generasi muda kita,” terang Gubernur SDK kepada penulis, Rabu 16 Juli 2025.
Melalui kebiasaan membaca buku yang konsisten, kata SDK, siswa secara bertahap akan mengasah kemampuan berpikir kritis dan memperdalam pemahaman isi bacaan. Ini sebuah modal penting dalam menghadapi banjir informasi di era digital yang tak selalu valid.
Program ini juga berpotensi menjadi tonggak awal membangun fondasi literasi digital secara integral. Misalnya, dengan menggabungkan buku fisik dan akses buku digital atau e-book, siswa terlatih tidak hanya untuk “membaca” tetapi juga “menyaring” informasi dan konten edukatif secara cerdas dan bertanggung jawab.
Namun, program ini menghadapi tantangan implementasi yang tidak ringan. Keberhasilan program sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas buku, peran aktif guru dan pengelola perpustakaan dalam membimbing siswa, serta dukungan keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, program hanya akan menjadi kewajiban administratif tanpa makna mendalam, bahkan bisa memunculkan kebosanan dan beban baru bagi siswa.
Oleh karena itu, pendampingan secara humanis dan metode penilaian yang menekankan pemahaman, diskusi, dan refleksi isi bacaan perlu dikembangkan. Jika dilihat dari segi dampak jangka panjang, program ini memiliki potensi besar untuk membentuk budaya literasi nasional yang kuat. Siswa yang terbiasa membaca secara teratur akan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga kritis dan kreatif dalam menganalisis berbagai informasi.
Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan nilai kebangsaan dan warisan budaya, sehingga menguatkan jati diri anak bangsa di tengah dinamika era digital dan globalisasi.
Quo vadis, Program Baca 20 Buku? Jika dijalankan dengan strategi komprehensif, mulai dari peningkatan akses buku berkualitas, penguatan perpustakaan, pelatihan guru, hingga keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat, maka program ini akan menjadi fondasi kuat menuju budaya literasi yang tangguh dan berkelanjutan.
Sebaliknya, tanpa kelengkapan sarana dan pendampingan mendalam, potensi program ini akan terbuang percuma, dan masalah rendahnya literasi akan tetap menjadi pekerjaan rumah berkepanjangan.
Kolaborasi sinergis antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas sangat diperlukan agar program baca 20 buku tidak sekadar menjadi target kuantitatif, melainkan menjadi gerakan literasi transformatif. Di era digital saat ini, membangun budaya membaca bukan hanya upaya mempertahankan warisan ilmu pengetahuan, tapi juga kemampuan hidup adaptif dan berdaya saing tinggi di dunia yang amat cepat berubah.
Program membaca di Eropa, Jepang, dan Cina sebagai contoh menunjukkan penyesuaian yang khas dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi (IT), dengan strategi yang tidak hanya mempertahankan budaya baca tradisional, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara adaptif.
Jepang tetap memiliki tingkat literasi baca yang tinggi meski teknologi berkembang pesat. Pemerintahnya mengembangkan berbagai program pendukung, seperti wajib membaca dan menceritakan buku di sekolah yang melibatkan guru dan siswa secara aktif. Selain itu, Jepang melengkapinya dengan fasilitas baca yang nyaman di ruang publik dan menggabungkan teknologi dalam program literasi, termasuk penerjemahan buku asing dan pengilustrasian digital yang menarik untuk meningkatkan kualitas bacaan.
Mereka juga memanfaatkan media digital dan kerja sama dengan tokoh populer melalui acara televisi bedah buku untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Ini menunjukkan integrasi harmonis antara kebiasaan membaca tradisional dan media digital sebagai alat edukasi dan hiburan.
Di Eropa, terutama di negara-negara seperti Finlandia, memadukan pendekatan literasi tradisional dengan teknologi melalui pengajaran berbasis self-discovery dan pembelajaran kolaboratif yang menggunakan platform digital. Sistem pendidikan Eropa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Selain itu, soal literasi digital dan akses ke e-book maupun sumber bacaan online diperluas untuk mempermudah akses informasi dan bacaan yang berkualitas. Kebijakan perpustakaan digital dan pelatihan guru pun diterapkan guna memastikan literasi berkembang menyeluruh di era teknologi modern.
Sementara Cina bergerak agresif dalam menggabungkan literasi dengan penguasaan teknologi digital sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan era AI. Pemerintah Cina mensinergikan bantuannya melalui program literasi yang menekankan penguasaan bahasa dan kemampuan literasi digital, termasuk pembelajaran berbasis aplikasi digital dan e-book yang terhubung dengan perkembangan teknologi informasi terkini.
Gerakan literasi di Cina menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme yang dikaitkan dengan kesiapan generasi muda berkompetisi di panggung global berbasis teknologi. Ketiga kawasan ini telah menunjukkan dinamika adaptasi program membaca terhadap kemajuan IT dengan pola yang kombinatif.
Nah, bila siswa di Sulbar dibebani 20 buku, guru-guru mereka tentu mesti lebih banyak. Apalagi aparatur birokrasi di pemerintahan agar ini berlaku seimbang dan paralel. Saya mengira ini salah titik penting quantum learing setelah Sulbar berusia dua dekade, agar bekas Afdeling Mandar terus dicatat dalam peradaban berkeadaban.
Ide besar yang ingin mengajak semua orang untuk membangun kebiasan membaca. Generasi cerdas dan terpelajar hanya lahir dari tradisi membaca yang tinggi. Sulawesi Barat sedang meniti di jalur yang jangka panjang. Biarlah program 20 Buku bakal ini diuji oleh konsistensi dan kesinambungan. (*)